 |
| Ilustrasi monyet ekor panjang. Sumber foto: https://mongabay.co.id/2018/07/01/ada-monyet-kegemukan-di-bali/ |
Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan salah satu gejala dari krisis ekologi, di mana ruang hidup dan sumber daya alam semakin terbatas. Di Indonesia, kasus yang masih terus terjadi adalah konflik antara masyarakat, khususnya petani, dengan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) atau MEP.
Konflik ini sering dinarasikan dengan mengidentifikasi MEP sebagai hama, penyebab gagal panen, dan ancaman bagi ketenangan warga. Sebuah anggapan yang mengaburkan akar permasalahan sesungguhnya, dan justru mendorong intervensi reaktif yang tidak efektif.
Secara biologis, MEP adalah primata yang sangat adaptif, bahkan menjadi spesies yang paling sukses dalam survival dan dapat hidup berdampingan dengan manusia. Mereka bisa tinggal di berbagai habitat, mulai dari hutan hingga lingkungan urban. Siklus hidup dan perkembangbiakannya tidak mengenal musim kawin yang spesifik, sehingga bisa melahirkan sepanjang tahun.
Kemampuan beradaptasi dan laju reproduksi yang relatif cepat tersebut juga ditunjang dengan pola makan yang dapat menyesuaikan lingkungan tinggalnya. MEP termasuk frugivora, atau pemakan buah alami, tapi juga bisa memakan biji-bijian, daun muda, bunga, hingga serangga. Bahkan, pola makan mereka dapat berubah drastis saat berinteraksi dengan manusia.
Mengurai Akar Masalah Konflik MEP dan Manusia
Sebagai satwa yang sangat adaptif, MEP cenderung memilih pakan yang menawarkan energi tinggi dengan resiko rendah dalam mendapatkannya. Lahan pertanian dan permukiman menjadi sasaran empuk karena menawarkan berbagai sumber pakan antropogenik yang mudah diakses dan memiliki kandungan kalori tinggi. Seperti buah-buahan, umbi-umbian, hingga sisa-sisa makanan manusia.Ketersediaan pakan yang melimpah dan mudah didapatkan ini, menciptakan perubahan pola perilaku mereka. Secara bertahap, MEP akan belajar dan mengaitkan kehadiran manusia dengan sumber makanan. Transformasi dari pemakan buah alami menjadi pemakan pakan non-alami ini menyebabkan ketergantungan dan berpotensi meningkatkan agresivitas terhadap manusia.
Ditambah lagi, ketersediaan pakan alami kini semakin terbatas akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan infrastruktur bangunan. Memicu perebutan ruang hidup antara manusia dan MEP yang semakin sengit. Seperti yang dilaporkan tim Relung Indonesia, terjadi di Paliyan, Gunungkidul, ratusan ekor MEP menyerang karena lahan pertanian karena masyarakat justru ikut memanen hasil dari tanaman buah di dalam Suaka Margasatwa Paliyan.
Ketergantungan pada pakan antropogenik, baik itu mencari di lahan pertanian, sisa sampah makanan, atau pemberian makanan oleh pengunjung wisata, memiliki konsekuensi yang jauh melampaui perubahan pola makan itu sendiri. Monyet akan kehilangan naluri alaminya dan menciptakan sebuah hubungan yang bersifat parasitisme.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Pakan yang dikonsumsi monyet dari tempat sampah, serta interaksi fisik yang dekat, dapat menjadi media penularan agen penyakit seperti tularemia, tuberkulosis, dan hepatitis.
Dengan demikian, konflik antara manusia dan monyet ekor panjang bukan hanya tentang kerugian ekonomi atau gangguan keamanan. Tapi juga ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat maupun spesies monyet itu sendiri.
Kesenjangan Ekologi dan Sosial sebagai Penyebab Kegagalan Intervensi Penanganan Konflik
 |
| Ilustrasi monyet ekor panjang membawa sampah. Sumber foto: pixabay.com |
Sebagai spesies primata non-manusia yang paling berhasil beradaptasi di berbagai habitat, MEP dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem. Namun, keberhasilan adaptasi ini menciptakan sebuah paradoks dalam perlindungan satwa.
Sejak Maret 2022, International Union for Conservation of Nature (IUCN) menaikkan status konservasi MEP dari vulnerable (rentan) menjadi endangered (terancam punah). Perubahan ini didasarkan pada tingkat perburuan, perdagangan, dan hilangnya habitat yang masif di berbagai negara yang menjadi wilayah jelajah MEP.
Meskipun status globalnya memprihatinkan, MEP belum masuk dalam daftar satwa yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018). Belum tegasnya regulasi ini semakin menjadi ancaman bagi keberadaaan MEP.
Status hukum yang lemah membuka pintu bagi perdagangan legal dan ilegal. Ribuan monyet diekspor untuk riset biomedis, diperdagangkan secara daring sebagai hewan peliharaan atau untuk pertunjukan. Perburuan kejam sering dilakukan dengan membunuh induknya untuk mengambil bayi-bayi monyet tersebut.
Di sisi lain, tanpa perlindungan hukum yang jelas, masyarakat yang frustrasi akan kedatangan MEP di wilayah perkampungan maupun ladang, cenderung mengambil tindakan sporadis. Monyet dipukul, diracun, atau bahkan dibunuh tanpa takut konsekuensi hukum.
Solusi yang lebih humanis seperti relokasi dan translokasi satwa liar, memang bisa menjadi pilihan. Namun, intervensi ini menghadapi tantangan dan membawa resiko besar bagi ekologi komunitas penerima dengan mengganggu keseimbangan populasi yang sudah ada.
Relokasi juga tidak akan benar-benar menyelesaikan akar masalah di lokasi asal jika fragmentasi habitat dan keterbatasan pakan tetap terjadi. Populasi yang tersisa akan terus mengalami konflik, atau masalah yang sama akan muncul kembali ketika monyet ekor panjang terus bereproduksi.
Pilihan kontrol populasi dengan sterilisasi juga sudah dilakukan. Seperti di Sangeh, Bali, dan di kota Lopburi, Thailand, yang menargetkan sterilisasi hingga 100% populasi. Namun, tanpa perbaikan ekosistem dan ketersediaan pakan yang memadai, populasi yang distabilkan akan terus menghadapi konflik karena dorongan untuk mencari makan di luar habitatnya tetap ada.
Pendekatan Ekologi, Ekonomi, dan Sosio-Kultur untuk Mendukung Koeksistensi
Upaya menghalau serbuan monyet ekor panjang di pemukiman warga tidak hanya butuh memahami sisi ekologi, tapi juga perlu meninjau aspek sosial budaya setempat. Karena MEP sering dianggap sebagai hama, maka untuk meminimalisir kegagalan program, dapat dilakukan dengan memetakan partisipasi masyarakat lokal.Petani adalah kelompok yang paling terdampak dan merasakan kerugian akibat konflik dengan MEP. Tanaman rusak, hasil panen menurun, dan secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan mereka. Oleh karena itu, ketika ingin memberikan solusi penangan konflik, terlebih dahulu perlu validasi kekhawatiran para petani.
Di beberapa daerah, petani bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga bagian dari struktur sosial yang punya kedudukan penting, seperti tokoh adat atau anggota perangkat desa. Belum lagi, mereka biasanya tergabung dalam keluarga kelompok tani yang jika teredukasi dengan baik dan merasa diuntungkan, efeknya bisa menyebar secara organik.
Sehingga, keberadaan petani menjadi kunci penting sebagai penghubung pengetahuan lokal dan basis legitimasi adat maupun sosial. Jika pendekatan solusi konflik hanya menambah beban pekerjaan, mereka bisa saja menolak. Maka, harus ada insentif langsung baik itu secara ekonomi atau keamanan hasil panen yang jelas terlihat dalam 1–2 musim tanam.
Oleh karena itu, perlu solusi yang menyentuh sisi ekologi, ekonomi, dan sosio-kultur. Di sinilah kita harus melampaui regulasi yang ada dan berfokus pada solusi praktis di tingkat akar rumput. Masa depan konservasi MEP tidak hanya terletak pada undang-undang, melainkan pada pemberdayaan masyarakat agar bisa menjadi penjaga bagi diri mereka dan satwa di sekitarnya.
Melalui model community-based human–primate conflict mitigation, solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah Desa Mandiri Konservasi. Sebuah program yang mencoba mengubah persepsi "monyet adalah musuh" menjadi "monyet adalah bagian dari ekosistem yang perlu dijaga." Program ini berfokus pada tiga pilar utama:
1. Pertanian yang Inovatif
Agar tidak terus merugi, petani diarahkan untuk menanam tanaman pengalih yang tidak disukai monyet. Seperti rempah-rempah, kopi, kakao, atau cabai di perbatasan lahan mereka. Di saat yang sama, sebagian lahan bisa ditanami dengan komoditas bernilai tinggi yang kebal dari serangan monyet, seperti porang atau umbi-umbian.2. Lahan untuk Koridor Pakan Alami
Dengan pendampingan tim konservasi, masyarakat dapat menanam pohon-pohon pakan alami yang disukai monyet di lahan yang jauh dari pertanian atau berbatasan dengan hutan. Koridor pakan ini akan berfungsi sebagai restoran alami bagi monyet, mengarahkan kawanan mereka untuk mencari makan di tempat yang aman dan menjauhi kebun-kebun petani.3. Komunikasi berbasis kearifan lokal
Pilar terpenting dalam mengimplementasikan sebuah program baru adalah komunikasi. Proses edukasi harus disampaikan dengan cara yang dapat diterima budaya lokal, misalnya melalui cerita rakyat, seni pertunjukan, atau forum diskusi komunitas. Apalagi, di beberapa daerah, adat lokal sering lebih dihormati dibanding hukum formal. Sehingga perlu menumbuhkan rasa empati dan kepemilikan masyarakat terhadap satwa di sekitar mereka dengan tetap menghormati adat dan budaya yang berlaku.Transformasi Alternatif untuk Praktek Eksploitasi
Mengingat secara hukum formal belum ada perlindungan khusus bagi monyet ekor panjang, celah untuk eksploitasi akan terus ada. Bahkan, ketika sudah dilindungi pun bukan berarti benar-benar bisa terlepas dari perburuan. Untuk itu, perlu adanya transformasi dalam lingkup sosial yang bisa menggiring perubahan perilaku dalam mengawal praktek eksploitasi.Dalam situasi ekonomi sekarang ini, alih-alih pelarangan yang mematikan mata pencaharian, tawarkan program transisi dengan pelatihan pemandu wisata yang lebih memperhatikan kesejahteraan satwa atau program pemantauan bersama hewan yang semula dipelihara dan direlokasi ke pusat rehabilitasi yang memenuhi standar. Pelarangan secara tiba-tiba cenderung memicu resistensi sosial. Seperti kemunculan pasar gelap yang menjadi lingkaran setan dalam perdagangan satwa.
Di era media sosial, juga perlu dilakukan pendekatan dengan pelatihan relawan untuk memantau dan melaporkan iklan jual beli primata secara online. Dengan adanya bukti digital, dapat digunakan untuk membantu penegakan dan pengungkapan rantai suplai, sehingga mampu mencegah terjadinya perdagangan yang lebih masif.
Konflik antara manusia dan MEP adalah cerminan dari ketidakseimbangan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Solusi reaktif seperti penangkapan, relokasi, atau sterilisasi yang sudah dilakukan tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan masalah ini. Pendekatan-pendekatan tersebut hanya mengobati gejala, mengabaikan penyebabnya, dan justru dapat memperburuk keadaan.
Solusi berkelanjutan terletak pada pengakuan bahwa koeksistensi mungkin untuk dilakukan. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan yang berpusat pada rekonsiliasi ekologi dan pembangunan kembali hubungan yang harmonis dengan alam. Mulai dari revitalisasi habitat, penciptaan koridor ekologi, dan edukasi yang berfokus pada perubahan perilaku manusia.
Lebih dari itu, solusi harus mengakar pada nilai-nilai dan kearifan lokal, di mana masyarakat ditempatkan sebagai mitra terdepan, bukan hanya objek dari program konservasi. Dengan demikian, kita dapat bertindak dengan berdasarkan pemahaman ilmiah, penghormatan budaya, dan partisipasi aktif yang berkelanjutan.
Referensi:
Farida, H., Perwitasari-Farajallah, D., & Tjitrosoedirdjo, S. S. (2019). Aktivitas Makan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta. Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati, 15(1), 24–30. https://doi.org/10.24002/biota.v15i1.2642
Eka Sahputra, Y. (2021, 4 Desember). Konflik Manusia dan Monyet di Batam Bisa Makin Parah Kala Hutan Terus Tergerus. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2021/12/04/konflik-manusia-dan-monyet-di-batam-bisa-makin-parah-kala-hutan-terus-tergerus/
IUCN Red List of Threatened Species. (2022). Macaca fascicularis. Diambil dari https://www.iucnredlist.org/species/195351957/221668305
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
Santosa, Yanto. (1996). Beberapa Parameter Bio-Ekologi Penting dalam Pengusahaan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Media Konservasi, V(1), 25-29. https://media.neliti.com/media/publications/231492-significant-bio-ecological-parameters-in-ae438a8d.pdf
Syah, M. J., Yuliastuti, & Safitri, M. (2024). Food Choices of Long-Tailed Monkeys (Macaca fascicularis) in the Pulaki Temple Area, Bali. Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology, 7(1), 35–44. https://doi.org/10.21580/ah.v7i1.20674
Farida, H., Perwitasari-Farajallah, D., & Tjitrosoedirdjo, S. S. (2019). Aktivitas Makan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta. Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati, 15(1), 24–30. https://doi.org/10.24002/biota.v15i1.2642
Eka Sahputra, Y. (2021, 4 Desember). Konflik Manusia dan Monyet di Batam Bisa Makin Parah Kala Hutan Terus Tergerus. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2021/12/04/konflik-manusia-dan-monyet-di-batam-bisa-makin-parah-kala-hutan-terus-tergerus/
IUCN Red List of Threatened Species. (2022). Macaca fascicularis. Diambil dari https://www.iucnredlist.org/species/195351957/221668305
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
Santosa, Yanto. (1996). Beberapa Parameter Bio-Ekologi Penting dalam Pengusahaan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Media Konservasi, V(1), 25-29. https://media.neliti.com/media/publications/231492-significant-bio-ecological-parameters-in-ae438a8d.pdf
Syah, M. J., Yuliastuti, & Safitri, M. (2024). Food Choices of Long-Tailed Monkeys (Macaca fascicularis) in the Pulaki Temple Area, Bali. Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology, 7(1), 35–44. https://doi.org/10.21580/ah.v7i1.20674

.webp)
.png)


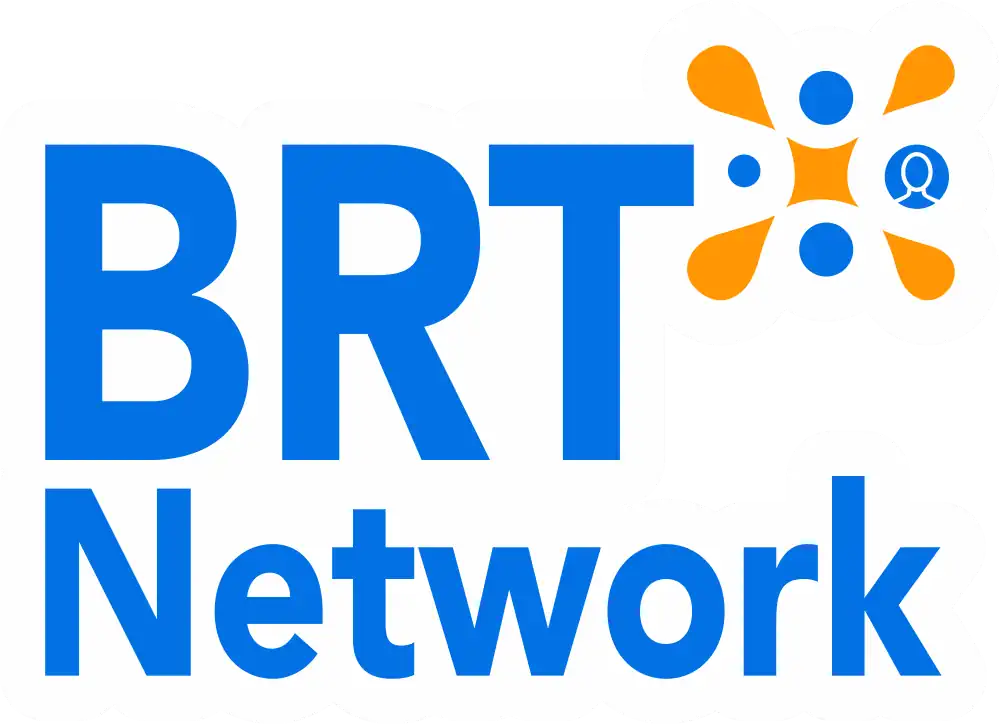


Posting Komentar
Posting Komentar