Setiap tanggal 2 Mei kita selalu merayakan Hari Pendidikan Nasional. Pemandangan serupa yang berulang adalah dari siswa sekolah dasar hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbaris rapi, menyimak pidato yang kadang penuh semangat tapi juga berisi refleksi, dan seremonial yang hampir tidak berubah dari tahun ke tahun.
Hari Pendidikan Nasional memang selalu dirayakan dengan penuh kebanggaan. Namun, di sela-sela kemeriahan itu, ada yang perlu kita renungkan: apakah benar-benar ada yang patut dirayakan dalam pendidikan kita hari ini?
Saya teringat cerita seorang teman yang berprofesi sebagai guru dan sempat mencicipi program SM3T. Ia mengajar di pelosok Flores, dengan ruang kelas sederhana dan buku-buku yang sudah menguning. Begitu kisah itu diulang-ulang hingga kini hampir 10 tahun berlalu.
Anak-anak didiknya datang tidak harus tepat pada jam 07.00. Jarak tempuh, cuaca yang tak menentu, membuat sekolah menerapkan jam fleksibel. Yang penting, di hari itu anak tetap bisa hadir di sekolah meski hanya 1 jam.
Ia juga kerap mengulang cerita tentang bagaimana harus menggambarkan airport dalam soal ujian nasional, kepada anak-anak yang melihat bus saja jarang. Apalagi melihat pesawat, apalagi ke bandara untuk menaikinya.
Pengalaman teman saya adalah refleksi dari perjalanan panjang pendidikan di negeri kita. Perjalanan yang penuh liku, harapan, dan juga paradoks. Ada banyak sekali masalah yang belum benar-benar tuntas diselesaikan, salah satunya adalah kesenjangan akses.
Napak Tilas Pendidikan Indonesia
Memperingati Hari Pendidikan Nasional alangkah baiknya diiringi dengan kembali menggali sejarah panjang dunia pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Hal ini bertujuan agar kita tidak lupa bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.Era Penjajahan: Ketika Pendidikan adalah Hak Istimewa
Di masa penjajahan, mendapatkan pendidikan formal ibarat memenangkan lotre, alias hanya segelintir orang yang beruntung saja yang dapat menikmatinya. Data sejarah mencatat, hingga tahun 1940, hanya sekitar 8% anak Indonesia yang bisa mengenyam bangku sekolah. Mereka pun sebagian besar berasal dari kalangan priyayi atau keluarga bangsawan yang dekat dengan pemerintah kolonial Belanda.Di tengah keterbatasan akses inilah, semangat pendidikan kebangsaan mulai berkobar dari gerakan-gerakan para pemuda. Hingga pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang sampai saat ini spiritnya masih kita rasakan. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
Sementara tokoh-tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah (1911) dan Mohammad Syafei dengan INS Kayutanam (1926) juga membangun fondasi pendidikan alternatif yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kesetaraan.
Setelah kemerdekaan, Indonesia masih belum sepenuhnya bisa merasakan pendidikan yang memadai karena mewarisi sistem yang rusak dan terbatas. Hampir 90% penduduk masih buta huruf. Namun, semangat membangun bangsa melalui pendidikan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, masih terus membara.
Sayangnya, mewujudkan pendidikan untuk semua bukan perkara mudah. Kondisi ekonomi yang masih sulit dan infrastruktur yang jauh dari layak, membuat pemerintah harus berjuang keras. Baru pada tahun 1950, UU No. 4 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran lahir sebagai kerangka sistem pendidikan nasional pertama.
Era Awal Kemerdekaan hingga Orde Baru: Membangun dari Puing-puing
Era Orde Baru (1966-1998) membawa angin segar bagi perluasan akses pendidikan. Melalui program SD Inpres yang dimulai tahun 1973, ribuan sekolah dasar dibangun hingga ke pelosok negeri. Data menunjukkan, dalam kurun waktu 1973-1979 saja, sekitar 31.000 SD Inpres didirikan dan angka partisipasi sekolah dasar melonjak dari 41% menjadi 85%.Namun di balik keberhasilan kuantitatif ini, pendidikan Orde Baru juga menyisakan kritik karena pendekatan sentralistik dan dogmatisnya. Kurikulum dirancang seragam dari Sabang sampai Merauke, dengan penekanan pada hafalan dan kepatuhan, bukan kreativitas dan pemikiran kritis.
Era Reformasi: Angin Perubahan dan Tantangan Baru
Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam lanskap pendidikan Indonesia. Desentralisasi menjadi kata kunci, dengan daerah memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi payung hukum baru yang membawa semangat demokratisasi pendidikan.Beberapa perubahan signifikan dalam periode ini antara lain:
- Pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (meski implementasinya baru terpenuhi di tahun 2009)
- Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah
- Program sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan
- Program perluasan akses seperti BOS, Kartu Indonesia Pintar, dan berbagai beasiswa
Kompleksitas sistem pendidikan yang sangat besar dan beragam, melibatkan lebih dari 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota, membuat pelaksanaan desentralisasi menghadapi tantangan besar dalam koordinasi dan efektivitas layanan pendidikan.
Potret Pendidikan Hari Ini: Krisis Literasi di Era Digital
Di tengah kemajuan teknologi dan perluasan akses pendidikan, Indonesia masih bergulat dengan tantangan mendasar terkait akses yang berdampak besar pada krisis literasi. Bayangkan, di era dimana anak-anak mahir mengoperasikan gadget canggih, banyak dari mereka masih kesulitan memahami teks sederhana.
Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menyajikan realitas yang memprihatinkan, dimana Indonesia berada di peringkat 73 dari 81 negara dalam kemampuan membaca, dengan skor rata-rata 359, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 476.
Selain itu, hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 juga mengungkapkan bahwa sekitar 50% siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca, bahkan di beberapa daerah angkanya bisa lebih tinggi. Data ini menegaskan kembali jika tantangan literasi di Indonesia masih sangat besar, baik di tingkat nasional maupun daerah terutama karena kesenjangan akses.
Paradoks ini semakin jelas ketika kita melihat penggunaan internet di kalangan remaja. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022 mencatat penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,01%, dengan jumlah pengguna internet sekitar 210 juta jiwa dari total populasi 272 juta jiwa.
Dalam survei tersebut juga disebutkan bahwa remaja usia 13-18 tahun adalah pengguna aktif internet yang paling hobi berselancar di dunia maya, dengan rata-rata penggunaan 7,5 jam per hari. Namun, aktivitas digital ini tidak berdampak positif pada kemampuan literasi mereka.
Tugas Guru di Tengah Krisis Literasi: Antara Beban Administratif dan Panggilan Jiwa
Guru sebagai tulang punggung pendidikan, juga menghadapi dilema tersendiri. Di satu sisi, tuntutan administratif semakin berat. Di sisi lain, kesempatan untuk pengembangan profesional dan fokus pada pengajaran berkualitas justru menjadi berkurang.Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2022 masih di bawah standar minimal yang ditetapkan, yakni 55, dengan rata-rata nasional hanya mencapai 54,05. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama karena kompetensi guru memegang peranan sentral dalam proses pengajaran dan berpengaruh pada motivasi belajar siswa.
Tentu ini bukan serta merta menjadi salah guru. Sistemlah yang membentuk mereka, mulai dari pendidikan calon guru hingga kebijakan di sekolah, yang belum sepenuhnya mendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi agar lebih berkualitas.
Dampak Pandemi Memperparah Luka yang Belum Pulih
Pandemi COVID-19 meninggalkan bekas luka yang dalam pada pendidikan Indonesia. Meski sekolah telah kembali tatap muka, dampak pembelajaran jarak jauh masih terasa hingga kini.Penelitian kolaboratif antara SMERU Research Institute dan UNICEF pada tahun 2022 mengungkap fenomena learning loss yang signifikan akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Estimasi kehilangan pembelajaran ini setara dengan 0,9 hingga 1,2 tahun sekolah.
Dampak learning loss ini paling parah dirasakan oleh siswa dari keluarga prasejahtera dan yang tinggal di daerah terpencil, yang menghadapi keterbatasan akses pembelajaran jarak jauh, seperti koneksi internet yang buruk dan minimnya interaksi langsung dengan guru.
Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa selama penutupan sekolah, waktu belajar siswa sangat terbatas (rata-rata 2,2 hingga 3,5 jam per hari), dan ketimpangan akses fasilitas pembelajaran semakin memperlebar kesenjangan hasil belajar antar siswa. Banyak guru di daerah terpencil tidak dapat mengajar secara efektif karena keterbatasan teknologi dan jaringan internet, sehingga metode pembelajaran lebih banyak berupa pemberian tugas tanpa interaksi aktif.
Tantangan Pendidikan Indonesia: Dari Kesenjangan hingga Kebijakan
Salah satu realitas pahit pendidikan Indonesia adalah kesenjangan yang masih menganga lebar. Akses dan kualitas pendidikan seringkali bergantung pada wilayah di mana seorang anak dilahirkan dan dibesarkan.Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Di daerah perkotaan, terdapat 49,16% penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA/sederajat. Sementara penduduk desa, hanya 27,98% yang menamatkan jenjang pendidikan SMA/sederajat.
Kesenjangan pendidikan ini akan berdampak pada human capital, dimana kualitas pendidikan dan kecocokan keterampilan menjadi modal untu mendorong produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada perekonomian banga.
Berdasarkan laporan McKinsey Global Institut (MGI), untuk beralih ke negara berstatus high-income, Indonesia perlu menaikkan pertumbuhan produktivitas (output per worker) tahunannya yang sejak tahun 2000 berada di angka 3,1% menjadi 4,9%. Sehingga, peran pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja sangatlah penting.
Belum lagi masalah terkait keterampilan yang dipelajari di sekolah sudah ketinggalan jaman dibanding kebutuhan industri sekarang. Kompetensi digital, pemecahan masalah kompleks, dan keterampilan komunikasi menjadi tiga keterampilan teratas yang sulit ditemukan pada lulusan Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara kurikulum pendidikan dengan tuntutan dunia kerja di era digital.
Program Makan Bergizi Gratis: Ketika Niat Baik Bertemu Prioritas yang Kurang Tepat
Di tengah berbagai tantangan pendidikan, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) dengan anggaran fantastis. Program ini bertujuan untuk memastikan siswa mendapat asupan gizi cukup untuk mendukung proses belajar mereka. Namun, menarik untuk menimbangnya dari sudut pandang prioritas dan efektivitas.Global Education Evidence Advisory Panel (GEEAP), telah mengklasifikasikan berbagai program pendidikan berdasarkan efektivitas biaya dan dampaknya, antara lain:
- Great buys: intervensi dengan dampak sangat besar dan biaya relatif rendah
- Good buys: intervensi dengan dampak positif dan biaya moderat
- Promising but low-evidence: intervensi yang menjanjikan namun bukti empirisnya masih terbatas
- Bad buys: intervensi dengan dampak minimal namun biaya tinggi
- Informasi yang disesuaikan dengan perkembangan anak tentang manfaat, biaya, dan kualitas pendidikan
- Pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa (teaching at the right level)
- Pengembangan profesional guru yang terstruktur dengan pendampingan dan umpan balik
Semestinya, masih banyak program yang bisa diupayakan yang termasuk dalam great buys untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, program MBG memiliki potensi manfaat, khususnya untuk wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Dari Sekolah Rakyat hingga Sekolah Unggulan Garuda: Potret Kesenjangan Baru
Paradoks pendidikan yang dulu pernah ada, kini hadir kembali. Pendidikan yang sering diharapkan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan, justru jadi celah memperpanjang jurang ketimpangan sosial. Realitas ini kembali mencuat saat pemerintah meluncurkan dua program baru, yaitu Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat.
Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, gagasan ini muncul dengan spirit memfasilitasi pendidikan untuk masyarakat yang hidup di garis kemiskinan dan membuka peluang pelajar berprestasi untuk bisa mengakses perguruan tinggi top dunia.
Sehingga, kemunculan 2 sekolah ini membagi sistem pendidikan Indonesia ke dalam tiga kategori, yaitu Sekolah Reguler (sekolah negeri pada umumnya), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan Garuda. Sekilas, tampak seperti upaya pemerataan akses. Namun, bila dicermati lebih dalam, sistem ini justru berisiko memperkuat stratifikasi pendidikan.
Sekolah Unggulan Garuda dirancang untuk menampung siswa-siswi dengan kecerdasan tinggi dari seluruh penjuru negeri. Dengan sistem pendidikan berasrama, kurikulum unggul, serta fasilitas kelas satu, sekolah ini diposisikan sebagai pencetak pemimpin masa depan. Dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan diharapkan menjadi jalan cepat generasi yang lebih siap dengan kompetensi global.
Namun, pertanyaannya, siapa yang benar-benar bisa masuk ke sana? Meskipun secara teori terbuka bagi siapa pun, dalam praktiknya, akses terhadap sekolah unggulan hampir selalu berpihak kepada mereka yang sejak awal memiliki keunggulan baik dalam ekonomi, literasi, lingkungan belajar, maupun bimbingan dari keluarga yang sadar pendidikan.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk afirmasi untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan menggunakan pendekatan asrama dengan jaminan gizi. Tujuan mulianya adalah memberi kesempatan bagi mereka yang selama ini nyaris tak tersentuh sistem pendidikan formal.
Lagi-lagi, tantangan besar mengintai. Kualitas guru, infrastruktur sekolah, kurikulum yang relevan, hingga koneksi ke perguruan tinggi dan lapangan kerja berkualitas masih menjadi tanda tanya. Tanpa standar, mutu yang setara dengan sekolah unggulan, Sekolah Rakyat dikhawatirkan hanya menjadi tempat penampungan.
Dari sudut pandang keadilan sosial, pendekatan dua kutub ini menimbulkan pertanyaan serius. Mengapa negara justru membagi pendidikan berdasarkan kemampuan awal dan latar belakang ekonomi? Seharusnya, seperti yang dikemukakan oleh filsuf John Rawls, sistem pendidikan perlu memprioritaskan mereka yang kurang beruntung agar memiliki peluang yang setara, bukan membuat kategori tersendiri dengan standar yang lebih rendah.
Untuk itu, reformasi kebijakan tidak cukup berhenti pada pembangunan gedung atau pengklasifikasian sekolah. Jangan sampai sekolah-sekolah ini hanya menjadi gengsi proyek antar kementrian. Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah ini juga bukan sekadar penghibur bagi masyarakat.
Siswa dari Sekolah Rakyat perlu mendapat akses afirmatif ke sekolah unggulan atau perguruan tinggi ternama dengan beasiswa penuh, pelatihan kesiapan akademik, dan pendampingan yang konsisten. Diperlukan juga program mentoring atau pertukaran siswa antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan bisa menjadi sarana pembelajaran lintas latar belakang, menumbuhkan empati, serta memperluas jaringan sosial siswa dari kelompok kurang beruntung.
Sebab, pendidikan adalah hak bagi semua. Jangan sampai kita justru sedang menggambar garis pembatas baru. Pemerataan pendidikan bukan sekadar wacana keadilan sosial, melainkan sebagai investasi utama dalam membangun bangsa yang tangguh, berdaya saing, dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Merayakan Harapan di Tengah Ketidakpastian
Di tengah berbagai tantangan yang ada, tentu terdapat banyak hal yang layak dirayakan dalam dunia pendidikan kita. Di berbagai pelosok Indonesia, tidak sedikit guru yang terus berjuang memberikan pendidikan terbaik meski dengan keterbatasan. Menjadi cahaya harapan yang patut kita rayakan.Banyak kelompok masyarakat yang masih memperjuangkan pendidikan yang lebih setara. Dari gerakan literasi di berbagai pelosok negeri, sekolah darurat untuk anak jalanan, hingga komunitas guru yang berbagi praktik pengajaran via media sosial, inisiatif akar rumput ini menjadi semangat hidup pendidikan Indonesia.
Beberapa perubahan kebijakan dalam dekade terakhir pun menunjukkan arah yang progresif. Walaupun selalu saja lekat dengan istilah ganti meneteri ganti kurikulum, namun menjadi pertanda bahwa kualitas pendidikan di Indonesia akan terus diperjuangkan.
Keberadaan Kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk mengadaptasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Asesmen Nasional yang bergeser dari ujian berbasis konten menuju asesmen kompetensi dan penghapusan penjurusan di SMA agar siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai kebutuhan adalah kebijakan yang dinilai lebih inklusif sekaligus menekankan keterlibatan berbagai pihak, termasuk orang tua.
Perubahan tersebut tidaklah sempurna, tapi juga upaya untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Namun sayangnya, lagi-lagi keberadaan Kurikulum Merdeka tetap saja tidak semua pihak menyukainya dan harus kembali ditinjau untuk diganti. Tapi sistem ini menjadi cerminan bahwa yang di perlukan sekarang ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi juga pengembangan kompetensi dan karakter.
Ditambah lagi, transformasi teknologi digital membuka peluang demokratisasi akses pendidikan berkualitas. Sekalipun menurut data Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tantangan utama masih berkisar pada terbatasnya konektivitas, karena 86% sekolah di Indonesia belum memiliki akses fixed broadband.
Berbagai inisiatif EdTech membuka kesempatan akses pembelajaran yang berkualitas tanpa terhalang jarak. Seperti Rumah Belajar dan Ruangguru, yang menyediakan kanal belajar bagi pelajar di berbagai tingkat dan kalangan, termasuk juga para guru.
Refleksi dan Harapan: Apa yang Patut Kita Rayakan dan Perjuangkan?
Saat kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, mungkin yang patut kita rayakan bukanlah kondisi sistem pendidikan kita yang masih penuh tantangan. Tetapi semangat dan resiliensi para pendidik, siswa, dan komunitas yang terus berjuang mewujudkan pendidikan yang lebih baik.
Terlebih sebagai orang tua, saya tidak bisa hanya mengandalkan sistem. Saya harus aktif terlibat dalam pendidikan anak-anak saya. Salah satunya dengan terus up-to-date terhadap kebijakan yang berlaku, mendukung sisi yang baik, dan melengkapi yang kurang dengan terus meningkatkan pendidikan di dalam rumah.
Beberapa hal yang perlu kita upayakan bersama diantaranya, mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas, memprioritas intervensi berbasis bukti yang terbukti paling efektif meningkatkan hasil belajar, merevitalisasi profesi guru sebagai ujung tombak transformasi pendidikan, dan emastikan teknologi menjadi alat pemersatu, bukan pembentuk kesenjangan baru.
Pendidikan adalah perjalanan panjang sebuah bangsa. Setiap pencapaian kecil, kita boleh saja merayakan sambil terus memperjuangkan perubahan yang lebih besar. Semangat inilah yang menjadi modal terbesar untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkualitas di masa depan.
Referensi:
- Adryamarthanino, Verelladevanka. (2021, 17 Agustus). Perkembangan Sejarah Pendidikan di Indonesia. Diakses pada 2 Mei 2025, dari https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/17/100000979/perkembangan-sejarah-pendidikan-di-indonesia.
- APJII. (2022, 9 Juni). APJII di Indonesia Digital Outloook 2022. Diakses pada 2 Mei 2025, dari https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outloook-2022_857.
- Faradianti, Merinda. (2025, 1 Mei). 5 Syarat RI Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi Menurut McKinsey. Diakses pada 2 Mei 2025, dari https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/69945/5-syarat-ri-jadi-negara-berpenghasilan-tinggi-menurut-mckinsey.
- Infopers. (2025, 29 Maret). Ketimpangan Pendidikan dalam Perspektif Keadilan Sosial: Kajian Kritis Dampak Sekolah Unggulan Garuda vs Sekolah Rakyat. Diakses pada 2 Mei 2025, dari https://infopers.com/ketimpangan-pendidikan-dalam-perspektif-keadilan-sosial-kajian-kritis-dampak-sekolah-unggulan-garuda-vs-sekolah-rakyat.
- Lim, D., Rarasati, N., Tresnatri, F. and Barasa, A.R. 2022. Learning Loss or Learning Gain? A Potential Silver Lining to School Closures in Indonesia. RISE Insight Series. 2022/041. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-RI_2022/041.
- OECD. (2023, 5 Desember). PISA 2022 Results (Volume I and II) - Country Notes: Indonesia. Diakses pada 2 Mei 2025, dari https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html.
- Tim SMERU Research Institute. (2022, Desember). Laporan Tahunan 2021. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- World Bank Group. (2018, 3 April). Improving Teaching and Learning in Indonesia. Diakses pada 2 Mei 2025, dari https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/improving-teaching-and-learning-in-indonesia

.webp)




.png)


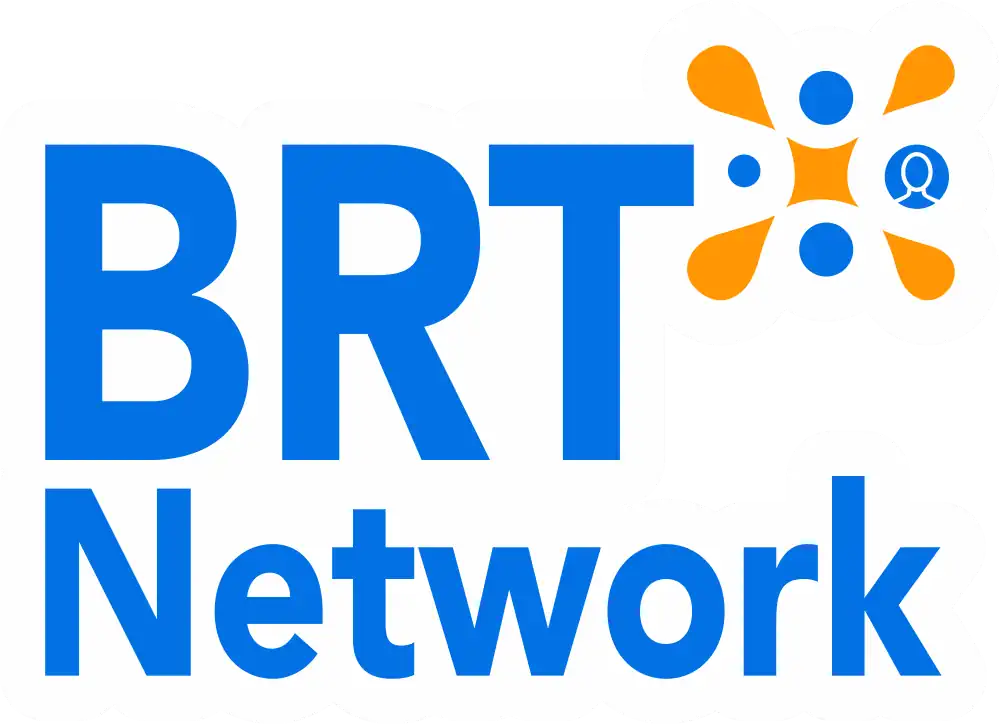


Posting Komentar
Posting Komentar